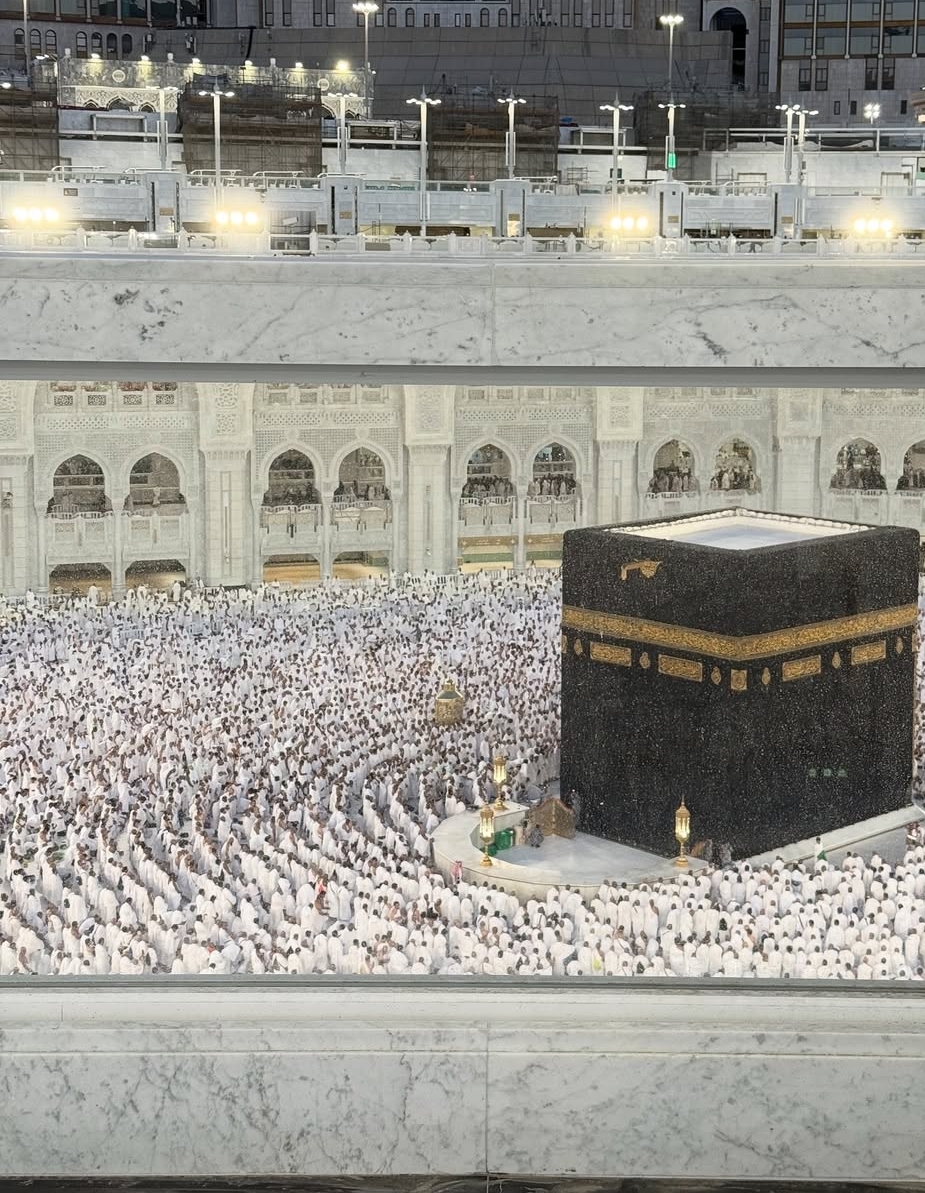#CeritaHK
ESQNews.id, JAKARTA - Aku masih ingat hari pertama bekerja di tim baru itu. Suasananya hangat, penuh tawa, dan seolah semua orang sudah saling mengenal. Boss kami, Pak Arif, dikenal sebagai sosok yang bersahabat.
Ia sering berkata, “Kita ini bukan atasan dan bawahan, kita ini teman.” Kalimat itu membuatku merasa aman… sampai akhirnya, aku menyadari bahwa “teman” ternyata tidak selalu berarti “mau mendengar.”
Masalah mulai muncul ketika kami mengerjakan proyek besar. Aku, sebagai koordinator lapangan, melihat bahwa jadwal kerja terlalu padat dan berisiko membuat tim kelelahan. Aku memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat.
“Pak, kalau kita paksakan ritmenya seperti ini, tim bisa burnout. Mungkin sebaiknya kita bagi dua tahap,” kataku hati-hati.
Pak Arif menatap layar laptopnya tanpa mengangkat kepala. “Kamu terlalu khawatir. Kita harus push sekarang, nanti bisa istirahat setelah selesai.”
Aku mencoba lagi beberapa kali, tapi jawabannya selalu sama, "Sudah, jalani saja.”
Lama-lama aku merasa bukan sedang bicara dengan teman, tapi dengan dinding.
Hari demi hari, tim mulai kelelahan. Beberapa rekan jatuh sakit. Aku melihat Rani, staf paling muda, menangis diam-diam di ruang pantry karena dimarahi akibat laporan yang telat.
Aku ingin bicara lagi, tapi bayangan tatapan dingin Pak Arif membuatku ragu.
Suatu malam, setelah lembur, aku duduk di parkiran sendirian. Keringat dan emosi bercampur jadi satu. Aku marah pada sistem, pada bossku, bahkan pada diriku sendiri.
Apa gunanya punya “teman” kalau tak pernah mau mendengar?
Beberapa hari kemudian, situasi makin kacau. Target belum juga tercapai, dan moral tim runtuh. Tapi di tengah tekanan itu, sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya.
Pak Arif datang pagi-pagi ke ruang kerja kami. Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. “Aku mau minta maaf,” katanya. Semua menatapnya heran.
“Aku pikir aku sudah jadi pemimpin yang terbuka. Tapi ternyata aku hanya mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Aku lupa kalau kalian bukan mesin, tapi manusia yang butuh didengarkan.”
Ruang itu mendadak hening. Aku menatapnya, setengah tak percaya. “Pak, kami tidak marah. Kami cuma… ingin punya ruang bicara,” ucapku lirih.
Ia tersenyum tipis. “Mulai sekarang, aku janji akan mendengarkan, benar-benar mendengarkan.”
Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Pak Arif mulai meminta pendapat sebelum memberi keputusan. Ia mendengar keluhan tanpa langsung menghakimi. Bahkan saat ada kesalahan, ia memilih bertanya dulu, bukan langsung menuding.
Kami belajar bekerja bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa percaya. Dan aku belajar sesuatu yang lebih dalam bahwa komunikasi tanpa empati hanya akan melahirkan jarak, dan jabatan tanpa hati hanyalah beban.
Kini, setiap kali aku memimpin rapat, aku selalu mengingat masa itu. Karena dulu aku pernah jadi orang yang tak didengarkan, aku tak mau menjadi pemimpin yang tuli terhadap timnya.
Kadang, “teman yang tak pernah mendengar” bukan hanya tentang atasan, tapi juga tentang diri kita yang sering mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami.
Kepemimpinan sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa dalam kita mau mendengarkan. Mendengar adalah bentuk tertinggi dari menghargai manusia lain.
Mari kita belajar menjadi pendengar yang tulus di tempat kerja, di rumah, dan dalam setiap hubungan. Karena sering kali, yang dibutuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang benar-benar mau memahami.
“Jika kamu ingin dipahami, mulailah dengan memahami.” – Socrates