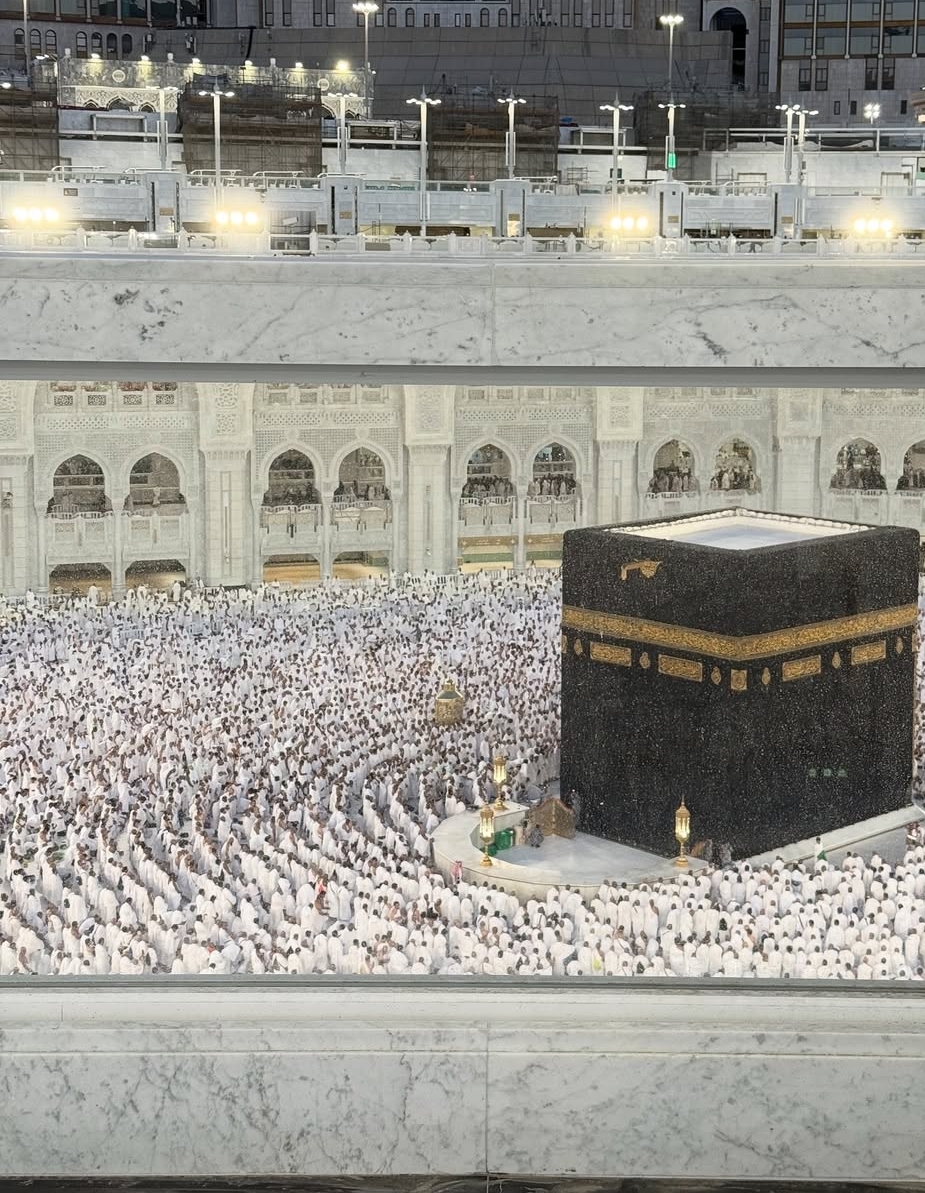KISAH
#CeritaHKESQNews.id, JAKARTA - Hari Senin pagi. Aku datang dengan langkah berat, menatap layar laptop yang penuh dengan notifikasi merah, deadline yang belum selesai, revisi dari boss, dan pesan singkat dari tim yang isinya cuma satu kata “capek.”Belakangan ini suasana tim kami memang seperti bom waktu. Banyak yang diam tapi wajahnya menyimpan jengkel. Dan penyebabnya, menurut mereka, hanya satu, Pak Ade. Boss kami.Ia dikenal perfeksionis, cepat marah, dan hampir tidak pernah tersenyum. Semua laporan harus rapi, semua ide harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data, semua kerja harus selesai “kemarin.”Aku, sebagai koordinator tim, sering jadi perantara antara keluhan anak-anak dan instruksi boss. Kadang aku sendiri bingung harus berdiri di pihak siapa.Pagi itu, kami rapat. Belum lima menit berjalan, suara Pak Ade sudah meninggi.“Kenapa progress-nya begini-begini saja?! Sudah dua minggu tidak ada perubahan signifikan!”Timku tertunduk. Aku mencoba menjawab dengan tenang, “Kami sedang berusaha, Pak. Ada beberapa kendala di lapangan yang belum bisa kami atasi.”“Alasan lagi! Semua orang bisa beralasan. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab?” bentaknya.Rasanya seperti disiram air panas. Ruangan hening. Hanya suara AC yang terdengar.Aku menarik napas panjang, lalu berkata, “Baik, Pak. Kami akan perbaiki.”Rapat selesai dengan wajah-wajah letih.Sore harinya, saat semua pulang lebih dulu, aku masih di meja kerja. Tiba-tiba Pak Ade muncul di belakangku. Aku spontan menegakkan badan.“Masih di sini?” tanyanya datar.“Ya, Pak. Sedang menyusun laporan tambahan.”Ia mengangguk, lalu menatap jendela yang mulai gelap. “Kamu tahu, kadang aku benci hari Senin,” katanya pelan.Aku kaget. Kalimat itu terdengar jujur, bahkan rapuh. Ia menatap jauh keluar jendela, lalu berkata lagi, “Aku marah bukan karena kalian tidak kerja keras. Aku marah karena aku takut. Takut gagal, takut mengecewakan perusahaan, takut kehilangan kepercayaan.”Suasana berubah hening. Aku tak tahu harus berkata apa.“Waktu muda, aku pernah gagal besar. Proyekku waktu itu ditutup karena aku terlalu percaya sama orang lain. Sejak itu aku jadi keras, mungkin terlalu keras. Aku pikir kalau aku menekan tim, hasilnya pasti maksimal. Tapi mungkin aku salah.”Aku baru sadar, di balik setiap suara bentakan dan wajah dinginnya, ada beban besar yang tak pernah terlihat. Ia bukan hanya mengatur tim, ia sedang berjuang melawan ketakutannya sendiri.“Pak,” kataku akhirnya, “kami juga takut gagal, tapi mungkin cara kita menanganinya berbeda. Kami butuh bimbingan, bukan hanya tekanan.”Ia menatapku lama, lalu menghela napas. “Kamu benar.”Malam itu, untuk pertama kalinya, kami bicara bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama berjuang.Keesokan paginya, suasana kantor berubah. Pak Ade memulai rapat dengan kalimat yang tak pernah kami dengar sebelumnya, “Saya minta maaf kalau selama ini terlalu keras. Saya hanya ingin kita tumbuh bersama, bukan saling menekan.”Beberapa rekan bahkan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada yang tertawa kecil, ada yang hanya menunduk sambil tersenyum.Dan sejak hari itu, kami bekerja dengan ritme baru. Ia tetap tegas, tapi tidak lagi menakutkan. Ia mulai mendengar, bukan hanya memerintah.Aku pun belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan di ruang training bahwa pemimpin juga manusia. Mereka bisa salah, bisa lelah, bisa takut, sama seperti kita.Kita sering menilai boss hanya dari cara mereka menekan, tanpa tahu beban yang mereka pikul. Tapi setiap orang punya sisi rapuh, bahkan mereka yang tampak paling kuat. Saat kita mau memahami, bukan hanya menuntut, hubungan kerja bisa berubah menjadi hubungan manusia yang saling menumbuhkan.Mari kita berhenti saling menyalahkan. Di dunia kerja ini, kita semua sedang belajar, baik sebagai pemimpin maupun anggota tim. Jika kita mulai dengan empati, mungkin suasana kantor tak lagi jadi medan perang, tapi ruang tumbuh bersama.“Sebelum menghakimi seseorang, cobalah berjalan sebentar dengan sepatunya.” – Mahatma Gandhi